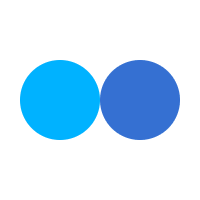Saat ini mitos antivaksin tersebar secara luas sehingga orang tua menjadi ragu untuk memvaksinasi anaknya. Berikut adalah mitos-mitos yang beredar dan bukti medis untuk mematahkan mitos-mitos tersebut.
Mitos: Vaksin Menyebabkan Autisme
Ketakutan mengenai kemungkinan vaksin menyebabkan autisme diperkirakan berasal dari sebuah studi oleh Andrew Wakefieldse, seorang dokter bedah dari Inggris yang telah dilarang berpraktik, yang mana studinya diterbitkan oleh sebuah jurnal medis prestisius, The Lancet, pada tahun 1997. Namun, artikel tersebut kemudian didiskreditkan dan ditarik dari publikasi karena ditemukan bukti konflik keuangan, kesalahan prosedur, dan pelanggaran etik.
Bahan di dalam vaksin yang dirumorkan dapat meningkatkan risiko autisme adalah thimerosal (etil merkuri). Namun, berdasarkan riset-riset yang diadakan oleh CDC, kandungan thimerosal di dalam vaksin tidak bersifat toksik dan hanya berperan sebagai pengawet. Tidak ada hubungan antara thimerosal di dalam vaksin dengan autisme. Selain itu, sejak tahun 1999, penggunaan thimerosal di dalam vaksin sudah dikurangi sebagai bentuk pencegahan.[1]
Riset lain membuktikan bahwa jumlah vaksin yang diterima oleh anak-anak sejak lahir hingga usia 2 tahun tidak berhubungan dengan risiko autisme. Jumlah vaksin yang diberikan dalam satu kali kunjungan juga tidak berhubungan dengan risiko autisme.[2]
Mitos: Sistem Imun Bayi tidak Bisa Mengatasi Berbagai Vaksin
Menurut CDC, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa pemberian beberapa vaksin secara bersamaan atau dalam waktu berdekatan dapat menyebabkan sistem imun bayi kewalahan atau mengalami gangguan. Dokter perlu menjelaskan kepada orang tua bahwa jumlah antigen di dalam vaksin jauh lebih kecil daripada antigen yang memapari anak setiap harinya di lingkungan.[3]
Mitos: Imunitas Alami Lebih Baik dari Imunitas yang Didapat dari Vaksin
Untuk mendapatkan imunitas alami, seseorang harus terjangkit penyakit tertentu dan kemudian sembuh. Pada beberapa kasus, imunitas alami dapat menghasilkan imunitas yang lebih kuat jika dibandingkan dengan vaksinasi.
Namun, jika seseorang ingin mendapatkan imunitas alami dari sebuah penyakit, sebagai contoh penyakit campak atau measles, berarti ia harus menghadapi kemungkinan kematian 1 di antara 500 kasus campak, padahal risiko efek samping vaksin lebih rendah.
Mitos: Vaksin Mengandung Bahan-bahan Toksik
Bahan-bahan yang diduga bersifat toksik di dalam vaksin adalah formaldehyde, thimerosal, aluminium, dan gelatin. Bahan-bahan tersebut memang bersifat toksik pada level tertentu, tetapi kadarnya di dalam vaksin tidak bersifat toksik.
Merkuri dalam Vaksin
Merkuri yang terkandung di dalam vaksin adalah etil merkuri yang berbeda dengan metil merkuri yang biasa ditemukan di ikan dan berbahaya bagi tubuh. Etil merkuri dimetabolisme dan diekskresi dari tubuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan metil merkuri. Tidak ada hasil riset yang membuktikan hubungan etil merkuri di dalam vaksin dengan autisme atau efek buruk lainnya.[3]
Formaldehyde dalam Vaksin
Formaldehyde di dalam vaksin digunakan untuk menonaktifkan virus dan menetralkan toksin bakteri. Menurut FDA dan CDC, sistem metabolik tubuh manusia menghasilkan lebih banyak formaldehyde jika dibandingkan dengan jumlah yang terkandung di dalam vaksin. Jumlah formaldehyde di dalam satu dosis vaksin hanya 0,02 mg, lebih sedikit jika dibandingkan dengan formaldehyde sebesar 1,1 mg yang secara alami ada di dalam sistem metabolisme bayi yang berusia 2 bulan.
Aluminium dalam Vaksin
Aluminium yang terkandung di dalam vaksin berfungsi untuk meningkatkan respon sistem imun sehingga dosis vaksin yang diberikan lebih sedikit. Dalam 6 bulan pertama kehidupan, bayi akan menerima 4 mg aluminium dari vaksin, yakni lebih sedikit dari jumlah aluminium yang didapat dari ASI (10 mg) atau dari susu formula (40 mg).[4]
Gelatin dalam Vaksin
Gelatin yang terkandung di dalam vaksin berguna untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kasus alergi yang disebabkan oleh gelatin di dalam vaksin sangat jarang terjadi, yaitu satu di antara 2 juta dosis vaksin.[5]
Di Indonesia, kandungan gelatin di dalam vaksin membuat beberapa orang tua meragukan kehalalannya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa mengenai imunisasi bahwa vaksin yang mengandung gelatin boleh digunakan pada kondisi darurat dan mendesak, pada saat belum ditemukan vaksin yang halal, dan saat tenaga medis menyatakan bahwa tidak ada vaksin pengganti yang halal.[6]
Mitos: Vaksin tidak Lagi Diperlukan karena Infeksi Sudah Menghilang akibat Kebersihan dan Sanitasi yang Baik
Vaksin memang bukan satu-satunya faktor yang dapat menghambat penyebaran infeksi. Nutrisi, kebersihan, sanitasi, dan faktor lainnya juga memegang peranan. Walau demikian, vaksin tetap memegang peranan penting. Walau demikian, data statistik menunjukkan bahwa vaksin memegang peranan penting sehingga tetap diperlukan.
Salah satu contoh adalah kejadian penyakit Haemophilus influenza tipe b (Hib) di Amerika Serikat yang menurun jauh setelah penggunaan vaksin. Angka turun dari sekitar 20.000 kasus per tahun menjadi 1419 kasus pada tahun 1993 meskipun tingkat sanitasi antara tahun 1990 sampai tahun 1993 tidak jauh berbeda.
Mitos: Risiko yang Diambil tidak Sebanding dengan Manfaat Vaksin
Tidak ada penelitian kredibel yang menyebutkan adanya efek buruk jangka panjang akibat vaksin. Berdasarkan laporan CDC, hanya ada satu kematian yang disebabkan oleh vaksin dari tahun 1990 sampai 1992. Kasus reaksi alergi terhadap vaksin secara umum hanya ada 1 kasus per satu juta sampai dua juta injeksi vaksin.[3,7]
Mitos: Vaksin Bisa Menginfeksi Bayi dengan Penyakit yang Berusaha Dicegah oleh Vaksin Tersebut
Vaksin bisa menyebabkan gejala yang mirip dengan penyakit yang kelak akan dicegah. Akan tetapi, gejala yang ditimbulkan bukan berarti bayi terinfeksi dengan penyakit yang ingin dicegah.
Pada kasus di mana timbul gejala setelah injeksi vaksin, yakni satu di antara satu juta kasus, penerima vaksin mengalami respon imun tubuh terhadap vaksin tersebut, bukan terhadap penyakit yang akan dicegah oleh vaksin.[3]
Di Amerika, hanya ada satu kasus dilaporkan mengenai vaksin yang menyebabkan infeksi penyakit, yakni vaksin polio oral. Sejak saat itu, vaksin sudah aman untuk digunakan selama beberapa dekade dan diawasi ketat oleh FDA.
Mitos: Vaksinasi tidak Diperlukan karena Tingkat Infeksi Beberapa Penyakit Sudah Rendah
Berkat vaksin, tercipta imunitas komunitas atau disebut herd immunity, yang berarti keadaan di mana tidak seratus persen orang dalam sebuah komunitas harus divaksinasi untuk dapat melindungi komunitas tersebut dari infeksi suatu penyakit. Hal ini penting untuk orang yang tidak bisa menerima vaksin, seperti orang yang menderita HIV/AIDS, orang dengan imunosupresi karena radioterapi atau kemoterapi, dan orang lanjut usia.[3]
Namun, studi menunjukkan bahwa jumlah orang tua yang mau memvaksinasi anaknya demi herd immunity tidak terlalu signifikan. Dokter sebaiknya menjelaskan kepada orang tua bahwa meskipun angka infeksi sudah rendah, bila vaksin dihentikan, ada kemungkinan beberapa penyakit yang masih terjadi dapat berkembang menjadi outbreak. Di negara di mana penyakit tersebut sudah hampir tidak ada pun, masih ada risiko bila ada turis yang berkunjung dari negara yang masih memiliki angka penyakit cukup tinggi.[3,8]
Kesimpulan
Untuk menghadapi orang tua yang ragu terhadap vaksin, dokter perlu mendengarkan semua pertanyaan dan kekhawatiran orang tua tersebut kemudian merespons dengan fakta yang sesuai. Edukasi juga dapat diberikan sebagai bagian rutin dari kunjungan pasien ke klinik anak-anak. Bila orang tua tetap menolak, dokter disarankan untuk mendokumentasikan hal tersebut dalam suatu surat pernyataan.[8,9]
Direvisi oleh: dr. Dizi Bellari Putri