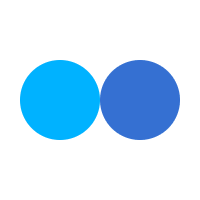Konstipasi kronis merupakan salah satu masalah gastrointestinal, dilaporkan bahwa 1 dari 3 orang lansia mengalami konstipasi kronis, dimana risiko meningkat jika pasien tinggal di panti werdha. Konstipasi kronis didefinisikan sebagai adanya konstipasi paling tidak selama 3 bulan dalam 1 tahun. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab gangguan kualitas hidup pada lansia.
Konstipasi kronis pada lansia diduga berhubungan dengan penurunan mobilitas, penggunaan polifarmasi, adanya penyakit dasar, dan disfungsi sensorik-motorik rektum. Konstipasi pada lansia umumnya dapat membaik dengan terapi nonfarmakologis. [1-3]
Diagnosis Konstipasi Kronis
Berdasarkan kriteria Roma IV, kriteria diagnosis konstipasi kronis adalah:
- Harus mengejan > 25% dari defekasi
- Feses keras atau menggumpal (skala Bristol tipe 1-3) > 25% dari defekasi
- Sensasi tidak tuntas > 25% dari defekasi
- Memerlukan manuver tertentu > 25% dari defekasi
- Defekasi < 3x/minggu
Diagnosis dapat ditegakkan apabila memenuhi 2 atau lebih kriteria dan berlangsung paling tidak selama 3 bulan dalam 1 tahun. [1,4]
Konstipasi kronis juga diklasifikasikan menjadi konstipasi primer atau fungsional dan konstipasi sekunder atau organik.
Konstipasi primer adalah kondisi dimana tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan dan penyebab konstipasi tidak dapat diidentifikasi, sedangkan konstipasi sekunder dapat disebabkan oleh adanya komorbiditas, misalnya ileus paralitik, ileus obstruktif, atau obat-obatan seperti loperamide dan loratadine.[2,4,5]
Red Flag Konstipasi Pada Lansia
Pada pasien lansia, tanda bahaya atau red flag konstipasi dapat menandakan adanya keganasan atau perdarahan gastrointestinal. Red flag ini di antaranya:
- Konstipasi dengan perdarahan per rektal
- Konstipasi dengan penurunan berat badan
- Perubahan pola defekasi
-
Riwayat keluarga kanker kolorektal atau inflammatory bowel disease
- Darah okult positif
- Defisiensi zat besi
- Konstipasi onset baru[2,5]
Tata Laksana Konstipasi Kronis
Pada pasien lansia, penyebab konstipasi kronis umumnya lebih dari satu faktor, sehingga pendekatan tatalaksana haruslah multifaktorial. [2-5] Tata laksana yang dapat diberikan adalah modifikasi diet, perubahan perilaku, dan tatalaksana farmakologis. Walaupun begitu, sekitar 75% konstipasi pada lansia dapat membaik dengan perubahan pola diet dan perilaku saja. [2,3]
Terapi Non-Farmakologis
Terapi awal konstipasi kronis pada lansia meliputi modifikasi diet dan perilaku. Modifikasi diet yang dilakukan adalah diet tinggi serat (25-30 gram per hari) dan konsumsi cairan 1,5-2,5 L per hari. Diet tinggi serat dan hidrasi yang baik dinilai dapat mempercepat waktu transit feses dalam kolon, sehingga mengurangi gejala konstipasi.
Terapi ini aman dan terjangkau, akan tetapi pada pasien lansia hal ini harus dilakukan dengan hati-hati dan secara gradual, terutama pada pasien gagal jantung dan penyakit ginjal. Bila terdapat impaksi feses, maka terlebih dahulu dilakukan disimpaksi dengan pemberian enema ataupun disimpaksi manual.
Pasien juga diedukasi untuk mengenali dan merespon setiap rasa ingin buang air. Rutinitas harian yang teratur, dimulai dengan aktivitas fisik ringan, sangat dianjurkan. Waktu optimal untuk buang air besar adalah setelah bangun tidur pagi dan setelah makan, yaitu waktu dimana usus besar meningkatkan aktivitas motoriknya.
Oleh karena itu, pasien disarankan untuk mencoba buang air besar di pagi hari setelah bangun tidur, dan dalam interval post prandial untuk memanfaatkan refleks gastrokolik sebaik mungkin
Selain itu, pemberian probiotik juga dapat membantu mengurangi konstipasi kronis pada lansia. Probiotik dinilai dapat mempersingkat waktu transit feses dalam kolon dan melunakan feses karena kandungan asam lemak pendek dalam probiotik yang tinggi. Salah satu meta-analisis dari 9 randomized clinical trial menunjukkan bahwa pemberian probiotik dapat memperbaiki gejala konstipasi pada lansia sebanyak 10%-40%.
Modalitas nonfarmakologis lainnya adalah meninjau penggunaan obat-obatan yang dipakai pasien. Apabila terdapat obat yang menimbulkan efek samping atau interaksi obat berupa konstipasi, maka penggantian atau penghentian obat perlu dipertimbangkan. Hal lain yang bisa dilakukan adalah mobilitas dan olahraga untuk memicu gerakan persitaltis. [2-4,6]
Terapi Farmakologis
Terapi farmakologis merupakan terapi lini kedua. Obat yang dapat diberikan adalah laksatif osmotik, bulking agent, laksatif stimulan, stool softener, dan agen prokinetik. Seluruh obat ini memiliki profil farmakologis, cara kerja, serta efek samping yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan untuk melunakan feses atau menstimulasi defekasi.
Terapi farmakologis dapat dimulai dengan pemberian laksatif osmotik dan atau bulking agent. Apabila tidak terdapat perbaikan, kombinasi laksatif stimulan dan pelunak tinja dapat diberikan. Pasien yang masih tidak menunjukkan perbaikan, sebaiknya dirujuk ke dokter spesialis.
Meskipun pilihan obat cukup variatif, sebagian besar pasien lansia yang mendapatkan terapi farmakologis berespon suboptimal. Penggunaan laksatif juga harus disesuaikan terhadap masing-masing pasien (tailored-therapy) dan dilakukan dengan hati-hati pada pasien lansia karena seringkali pasien lansia mengkonsumsi banyak obat lain. [1-4,7]
Perbandingan Jenis Laksatif Untuk Konstipasi Kronis pada Lansia
Untuk konstipasi kronis, dapat diberikan laksatif osmotik, seperti sorbitol, laktulosa, magnesium sulfat, dan polietilen glikol (PEG). Uji klinis menunjukkan bahwa laktulosa lebih baik dibandingkan sorbitol dalam memperbaiki pergerakan usus, tetapi perbedaan ini tidak cukup signifikan.[1-3,8,9]
Meta-analisis Cochrane menunjukkan bahwa penggunaan PEG lebih baik dibandingkan laktulosa dalam konstipasi kronis untuk meningkatkan frekuensi defekasi, memperbaiki bentuk feses, dan meredakan nyeri perut.[10]
Penggunaan laksatif osmotik PEG dilaporkan lebih baik dibandingkan bulking agent. Sebuah randomized controlled trial (RCT) pada 126 pasien dengan usia rata-rata 51 tahun, menunjukkan bahwa PEG lebih baik dibandingkan psyllium dalam memperbaiki pergerakan usus dan perbaikan skala Bristol (92.1% vs 73.0%). Keduanya tidak menunjukkan adanya efek samping yang signifikan.[11]
Studi mengenai perbandingan laksatif stimulan masih minimal, khususnya pada pasien geriatri. Meta analisis dari 2 buah uji klinis menunjukkan bahwa penggunaan senna kombinasi dengan bulking agent lebih baik dibandingkan laktulosa. Penggunaan senna juga aman dan tidak menimbulkan efek samping yang signifikan.[8]
Bisakodil dinilai sebagai agen laksatif stimulan yang lebih baik dalam memperbaiki frekuensi defekasi. Studi literatur menunjukkan bahwa bisakodil lebih efektif dibandingkan plasebo. Namun lebih banyak menyebabkan efek samping, terutama diare.[2,4,11]
Laksatif stimulan memiliki profil efek samping yang lebih banyak dibandingkan laksatif osmotik, seperti gangguan elektrolit, diare nyeri perut, dan melanosis koli, sehingga penggunaan laksatif osmotik lebih dianjurkan sebagai terapi farmakologis lini pertama.[1,11]
Studi mengenai agen prokinetik, enema, serta suppositoria dalam manajemen konstipasi kronis lansia masih sangat minimal. RCT pada 123 pasien menunjukkan bahwa penggunaan laktulosa atau laktulosa kombinasi dengan gliserin supositoria tidak memiliki perbedaan efektifitas yang signifikan.[12]
Agen prokinetik (agonis reseptor serotonin 5-HT4) juga dinilai dapat memperbaiki frekuensi defekasi dengan mempercepat waktu transit gastrointestinal. Namun efek samping kardiovaskular yang ditimbulkan cukup tinggi, sehingga penggunaan prokinetik masih harus dipelajari lebih lanjut, khususnya pada lansia.[4,8]
Kesimpulan
Konstipasi kronis merupakan kondisi yang sering ditemui pada lansia. Sebagian besar kasus dapat membaik dengan tatalaksana nonfarmakologis, berupa modifikasi diet dan perilaku. Pasien diminta untuk memperbanyak serat saat makan dan konsumsi cairan yang cukup. Pasien juga diedukasi mengenai bowel habit yang baik, yaitu mengusahakan buang air besar saat pagi hari setelah bangun tidur dan post prandial.
Terapi farmakologis dapat diberikan jika terapi nonfarmakologis gagal memperbaiki kondisi pasien. Pemberian laksatif sebaiknya disesuaikan terhadap setiap pasien (tailored-therapy) dan dilakukan dengan hati-hati, terutama pada pasien dengan penyakit jantung dan ginjal.
Jika pasien sudah mendapat terapi farmakologis adekuat tetapi tidak menunjukkan adanya perbaikan gejala, atau pada pasien yang memiliki red flag, pemeriksaan lanjutan dan rujukan ke spesialis gastroenterologi harus dipertimbangkan.