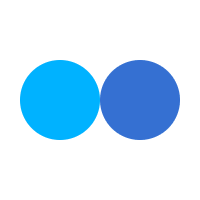Angka penggunaan dialisis peritoneal di Indonesia dilaporkan masih sangat rendah meskipun angka penderita penyakit ginjal kronis dilaporkan meningkat. Hemodialisis masih menjadi pilihan utama dialisis, sedangkan dialisis peritoneal jarang ditawarkan sebagai opsi bagi pasien. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini.[1-3]
Penyakit ginjal kronis (PGK) merupakan penyakit kompleks yang menyerang 13,4% dari populasi di dunia. PGK berkembang pesat seiring dengan meningkatnya populasi lanjut usia dan peningkatan prevalensi diabetes mellitus tipe 2, obesitas, hipertensi dan penyakit kardiovaskular lainnya. Seiring dengan perjalanan penyakitnya, PGK dapat menimbulkan disfungsi ginjal dan berkembang menjadi penyakit ginjal stadium akhir di mana pasien hanya dapat diterapi dengan terapi pengganti ginjal.[2,3]
Berdasarkan data Indonesia Renal Registry (IRR) pada tahun 2018, terdapat 132.142 pasien aktif yang mendapat terapi pengganti ginjal dengan peningkatan jumlah pasien baru hingga 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya pasien dengan kebutuhan terapi pengganti ginjal, perlu dipertimbangkan terapi pengganti ginjal yang bersifat berkesinambungan, efektif, serta mudah diakses di Indonesia.[2,3]
Saat ini, ada tiga opsi terapi pengganti ginjal untuk pasien penyakit ginjal stadium akhir, yaitu dialisis peritoneal, hemodialisis, dan transplantasi ginjal. Hemodialisis merupakan modalitas yang paling banyak digunakan di Indonesia, tetapi jumlahnya masih terbatas terutama di daerah yang terpencil. Ketersediaan donor ginjal untuk transplantasi ginjal juga merupakan isu yang lebih sulit. Oleh sebab itu, dialisis peritoneal diharapkan dapat lebih diperkenalkan dan digunakan sebagai terapi pengganti ginjal di Indonesia.[1,2]
Dialisis Peritoneal sebagai Terapi Pengganti Ginjal
Dialisis peritoneal adalah proses difusi dan ultrafiltrasi dari kompartemen darah yang banyak mengandung toksin uremik ke dalam cairan dialisat peritoneal melalui membran peritoneum (membran semipermeabel) yang bersifat hiperosmolar. Terdapat dua jenis dialisis peritoneal yaitu CAPD (continuous ambulatory peritoneal dialysis) dan APD (automatic peritoneal dialysis). Namun, saat ini hanya CAPD tersedia di Indonesia.[3,4]
Berbagai studi menunjukkan bahwa dialisis peritoneal mempunyai banyak keuntungan, seperti komplikasi yang lebih sedikit, teknik yang lebih sederhana, fleksibilitas yang lebih baik karena dapat dilakukan di rumah, biaya yang lebih ekonomis, dan kualitas hidup yang lebih baik daripada hemodialisis.[3-5]
Sebanyak 60–70% pasien mengalami komplikasi setelah hemodialisis dalam durasi waktu tertentu. Beberapa pasien juga mengalami kesulitan untuk menjangkau fasilitas kesehatan karena hemodialisis hanya bisa dilakukan di fasilitas tertentu. Pasien juga dihadapkan dengan banyaknya pantangan terutama restriksi cairan dan makanan, serta perlu konsumsi beberapa obat untuk memastikan kondisi hemodinamik stabil.[3-5]
Contoh efek samping setelah hemodialisis adalah hipotensi, mual, muntah, kejang otot, sakit kepala, nyeri dada, perdarahan di area akses hemodialisis, ketidakseimbangan hemodinamik, dan kelelahan. Namun, terlepas dari berbagai limitasi ini, hemodialisis masih lebih populer daripada dialisis peritoneal. Padahal, dialisis peritoneal memiliki lebih sedikit pantangan dan risiko.[3-5]
Pasien dapat melakukan dialisis peritoneal secara mandiri ataupun dengan bantuan keluarga di rumah masih-masing asalkan telah diberikan pelatihan, sehingga proses dialisis dilakukan secara aman, benar, dan berkesinambungan.[3-5]
Pemilihan Kandidat Dialisis Peritoneal
Dari sisi indikasi, dialisis peritoneal dapat dilakukan pada pasien dengan PGK stadium akhir yang mengalami tanda sindrom kelebihan cairan, sindrom uremikum, gangguan malnutrisi, dan gangguan elektrolit.[3-5]
Sementara itu, dialisis peritoneal tidak disarankan pada pasien yang memiliki riwayat luka luas area abdomen, hernia abdomen yang tidak dapat dikoreksi, riwayat inflamasi dan tumor area perut, serta fistula antara rongga peritoneum dan pleura. Pada pasien dengan riwayat operasi berulang di area perut atau riwayat tumor, inflamasi, dan hernia di area perut, risiko infeksi pada dialisis peritoneal akan menjadi lebih tinggi.[3-5]
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dialisis peritoneal lebih sedikit menimbulkan komplikasi dibandingkan hemodialisis. Namun, perlu persiapan baik dari sisi pasien, dokter spesialis penanggung jawab, dan keluarga untuk membuat dialisis peritoneal berhasil. Target keberhasilan diukur berdasarkan tidak adanya perubahan terapi pada pasien, adanya peningkatan kualitas hidup, dan tidak adanya infeksi.[1,6]
Dokter perlu memberi penjelasan dan pelatihan kepada pasien dan keluarga minimal selama 5 hari atau sampai pasien dan pendamping bisa melakukan dialisis peritoneal dengan baik dan benar. Pasien juga harus memahami proses perawatan akses dialisis peritoneal dan memahami tanda serta gejala kapan harus ke fasilitas kesehatan.[1,6]
Efektivitas Biaya Dialisis Peritoneal
Pada tahun 2014, dialisis menduduki peringkat kedua beban BPJS dengan biaya tertinggi. Suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan efektivitas biaya CAPD dan hemodialisis pada pasien di RSUD Hasan Sadikin Bandung. Data dikumpulkan dari Departemen Urologi periode tahun 2014–2017.[6]
Penelitian observasional retrospektif tersebut dilakukan pada 3 kelompok pasien, yaitu: pasien dengan CAPD yang efektif, pasien yang telah mengalami perbaikan CAPD dan terus menggunakan CAPD, serta pasien dengan CAPD yang mengalami pergantian terapi. Hasil studi menunjukkan penurunan biaya yang cukup signifikan pada semua kelompok pasien bila dibandingkan dengan biaya hemodialisis.[6]
Kendala Dialisis Peritoneal di Indonesia
Biaya dialisis peritoneal umumnya lebih terjangkau daripada hemodialisis. Akan tetapi, dialisis peritoneal tetap membutuhkan biaya yang tidak murah, terutama karena cairan dialisatnya mayoritas masih perlu diimpor. Terdapat cairan dialisat yang diproduksi lokal tetapi hal ini hanya mencakup 4–5% dari total suplai dialisis peritoneal di Indonesia. Harga cairan dialisat lokal ini juga tidak berbeda jauh dengan harga impor, karena beberapa bagian dari produksinya masih perlu diimpor.[1]
Masalah reimbursement dan insentif untuk tenaga kesehatan juga menjadi faktor. Saat ini, peraturan reimbursement dari pemerintah dan juga insentif untuk tenaga kesehatan lebih condong pada hemodialisis daripada dialisis peritoneal. Rumah sakit cenderung untuk mendirikan pusat hemodialisis daripada dialisis peritoneal, karena lebih profitable. Selain itu, tenaga kesehatan juga mendapatkan insentif jika melakukan hemodialisis.[1]
Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan di bidang nefrologi juga menjadi kendala, karena waktu untuk melakukan edukasi dan pelatihan bagi pasien dialisis peritoneal menjadi terbatas. Selain itu, masih ada tenaga kesehatan yang beranggapan bahwa dialisis peritoneal hanya ditujukan untuk pasien yang tidak bisa menerima hemodialisis. Tingkat kesadaran tentang dialisis peritoneal masih rendah, tidak hanya di masyarakat tetapi juga di kalangan tenaga kesehatan.[1]
Terdapat juga masalah sentralisasi, di mana distribusi dialisis peritoneal hanya berpusat di Jawa. Sekitar 64% unit dialisis peritoneal berlokasi di Jawa. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga distribusi alat ke pulau-pulau di luar Jawa memakan biaya yang cukup tinggi.[1]
Strategi untuk Meningkatkan Penggunaan Dialisis Peritoneal
Strategi ini perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit, hingga pemerintah. Untuk mengurangi biaya dialisis peritoneal, pemerintah dapat meningkatkan dukungan untuk produksi dialisat dan perlengkapannya di dalam negeri. Selain itu, pemerintah dapat mencanangkan peraturan atau rekomendasi agar dialisis peritoneal menjadi pilihan pertama sebelum hemodialisis jika pasien butuh terapi pengganti ginjal.[1]
Pemerintah dan manajemen rumah sakit juga bisa memperbaiki sistem reimbursement dan insentif agar lebih mendorong tenaga medis untuk melakukan dialisis peritoneal. Peningkatan insentif di area terpencil terutama dapat menghasilkan efek desentralisasi sumber daya yang terpusat di Jawa.[1]
Tenaga kesehatan juga perlu mendapatkan edukasi tentang dialisis peritoneal, agar tidak ada miskonsepsi bahwa dialisis peritoneal hanya ditujukan untuk pasien yang tidak bisa menjalani hemodialisis. Selain itu, tenaga kesehatan diberi pelatihan tentang metode, manfaat, dan risiko dialisis peritoneal, sehingga dapat meneruskan edukasi ke masyarakat. Tenaga kesehatan juga diedukasi untuk meningkatkan upaya skrining PGK agar pasien terdeteksi lebih dini.[1]
Informasi tentang dialisis peritoneal perlu lebih disebarluaskan, termasuk menggunakan televisi, media digital, dan telemedicine. Selain itu, pusat-pusat dialisis di Indonesia juga dapat bekerja sama dengan pusat dialisis peritoneal di luar negeri, yang memungkinkan konsultasi dan pertukaran ilmu dengan tenaga ahli dari luar.[1]
Kesimpulan
Dialisis peritoneal mempunyai beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan proses hemodialisis, yaitu biaya yang relatif lebih terjangkau, komplikasi yang lebih sedikit, dan teknik yang lebih sederhana. Dialisis peritoneal juga lebih fleksibel dan dapat dilakukan secara mandiri oleh pasien atau pengasuh di rumah setelah pelatihan.
Namun, saat ini masih ada beberapa kendala yang menyebabkan angka penggunaan dialisis peritoneal di Indonesia rendah. Contohnya adalah bahan dan alat yang masih perlu diimpor dari luar negeri, reimbursement dan insentif yang masih lebih mendukung hemodialisis, dan kesulitan distribusi ke luar Jawa. Tingkat kesadaran tentang dialisis peritoneal juga masih rendah, baik di kalangan medis maupun di masyarakat.
Peningkatan penggunaan dialisis peritoneal memerlukan kerja sama antara pemerintah, rumah sakit, dan tenaga kesehatan. Pemerintah dapat memberikan dukungan untuk meningkatkan produksi alat dan bahan dalam negeri, dan mengubah kebijakan terkait reimbursement dan insentif dialisis peritoneal. Insentif terutama perlu ditingkatkan di area terpencil, agar mengurangi sentralisasi di Jawa. Pelatihan untuk tenaga kesehatan juga diperlukan, sehingga tenaga kesehatan bisa meneruskan edukasi ke masyarakat.