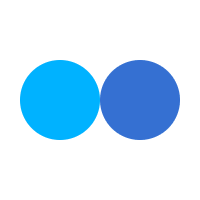Reaksi alergi dan anafilaksis terkait vaksin COVID-19 harus diperhatikan dokter untuk memberikan tata laksana yang tepat kepada masyarakat. Vaksin COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) telah diakui sebagai intervensi terbaik untuk mengatasi pandemi ini, tetapi disisi lain terdapat laporan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi) untuk reaksi alergi ringan hingga anafilaksis.Reaksi alergi berat seperti anafilaksis pada pasien pasca vaksin COVID-19 ditemukan kurang dari 1 per 1.000.000 dosis. KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi) yang dilaporkan umumnya tidak serius dan tidak selalu dapat terjadi kembali pada paparan ulang. Sebagian besar efek samping setelah imunisasi (KIPI) adalah konsekuensi dari vaksin yang merangsang respons imun protektif, dan bukan alergi dalam etiologinya.[1,2]
Mekanisme Alergi pada Vaksin COVID-19
Meskipun reaksi lokal umumnya dapat dikaitkan dengan antigen aktif dalam vaksin, reaksi alergi yang terkonfirmasi akibat vaksin lebih sering disebabkan oleh sisa protein non manusia, pengawet, atau penstabil dalam formulasi vaksin yang dikenal sebagai eksipien. Eksipien diperlukan dan ditambahkan ke vaksin untuk tujuan tertentu, seperti merangsang respons imun yang lebih kuat, mencegah kontaminasi oleh bakteri, atau menstabilkan potensi vaksin selama transportasi dan penyimpanan.[2]
Terdapat dua eksipien alergen potensial utama dalam vaksin COVID-19 yaitu polietilen glikol (PEG) dan polisorbat 80. PEG dikenal juga sebagai makrogol yang juga digunakan dalam berbagai obat pencahar dan formulasi injeksi seperti steroid. Polisorbat 80 digunakan sebagai surfaktan, penstabil dan pengemulsi dalam komposisi: kosmetik, deterjen dapat ditemukan dalam berbagai produk medis, seperti krim, salep, lotion, dan tablet obat.[2,3,11]
Kontraindikasi pemberian vaksin COVID-19 termasuk riwayat reaksi anafilaksis sebelumnya terhadap dosis pertama vaksin COVID-19 atau terbukti hipersensitif terhadap komponen vaksin, seperti PEG atau polisorbat 80. Anafilaksis atau reaksi alergi lainnya setelah imunisasi dapat menyebabkan ketakutan dan hilangnya kepercayaan terhadap keamanan vaksin di kalangan masyarakat. Pemahaman yang lebih baik mengenai reaksi alergi dapat meringankan kekhawatiran mengenai vaksin COVID-19 dan menganalisis insiden anafilaksis dengan tepat agar dapat dicegah dan dikelola dengan baik.[2]
KIPI Reaksi Alergi Vaksin COVID-19
Reaksi alergi yang dikonfirmasi terhadap vaksin biasanya tidak disebabkan dengan bahan aktif melainkan bahan tidak aktif yang dikenal juga sebagai eksipien seperti protein telur, gelatin, formaldehida, thimerosal, dan neomisin. PEG dari vaksin berbasis mRNA dan polisorbat 80 dari vaksin vektor virus telah diakui sebagai eksipien alergi utama.[1,4]
Tingkat reaksi alergi terkait vaksin umumnya tidak berat, faktanya risiko anafilaksis sangat rendah, terjadi dalam 1 dari 1.000.000 dosis vaksin. Namun, reaksi anafilaksis berpotensi mengancam nyawa dan berlangsung sangat cepat dalam hitungan menit setelah terpapar vaksin. Bahkan reaksi alergi ringan juga dapat menyebabkan komplikasi serius. Oleh karena itu, pengetahuan medis, perhatian, pencegahan, dan manajemen yang tepat sangat diperlukan.[1,4,5]
Reaksi alergi terkait vaksin COVID-19 dapat mempengaruhi bagian tubuh mana pun, termasuk kulit, pernapasan, kardiovaskular, dan gastrointestinal. Reaksi alergi ringan hingga sedang berupa reaksi lokal yaitu kemerahan, urtikaria lokal atau umum, takikardia, mual, dan diare.[2,6]
Reaksi anafilaksis dapat mengancam nyawa, dikarenakan adanya gangguan jalan nafas dan sirkulasi (hipotensi akut, spasme bronkus, dan edema laring) yang terjadi setelah paparan alergen. Untuk menegakkan diagnosis anafilaksis harus memenuhi 3 karakteristik klinis onset mendadak, perkembangan yang cepat, dan keterlibatan dua atau lebih sistem organ.[7]
CDC Report Terkait KIPI
Dalam laporan Centres for Disease Control and Prevention (CDC) yang menganalisis KIPI alergi terkait dengan vaksin COVID-19 Pfizer, dari 137 juta dosis yang diberikan terdapat 175 laporan kasus kemungkinan reaksi alergi yang dapat terjadi, 86 (49%) diantaranya tergolong reaksi alergi non anafilaksis dan 61 (35%) bukan merupakan reaksi alergi. Dalam waktu yang bersamaan, laporan mengenai vaksin COVID-19 Moderna, dari 111 juta dosis vaksin yang diberikan, terdapat 108 laporan kasus kemungkinan reaksi alergi, 43 (40%) tergolong reaksi alergi non anafilaksis dan 47 (44%) bukan merupakan reaksi alergi.[2]
Pada hari pertama setelah dilakukan vaksinasi massal dengan vaksin COVID-19 Pfizer, terdapat laporan anafilaksis di Inggris dan Amerika Serikat. Diperkirakan insidens anafilaksis terkait vaksin vaksin COVID-19 Pfizer sebesar 0,5 kasus setiap 100.000 dosis. Sedangkan perkiraan insidens anafilaksis vaksin lain berbasis mRNA sebesar 0,25-1,11 kasus setiap 100.000 dosis. Selanjutnya CDC melaporkan terdapat total 66 kasus anafilaksis di antara 17.524.676 dosis yang diberikan diantara 14 Desember 2020 – 18 Januari 2021 yaitu sebesar 0,37 kasus per 100.000 dosis.[2]
Kontraindikasi Vaksin COVID-19 pada Pasien Dengan Penyakit Alergi.
Secara umum, tidak ada kontraindikasi pemberian vaksin COVID-19 pada populasi dengan penyakit alergi lainnya. Namun, perhatian khusus harus diberikan kepada pasien dengan riwayat reaksi alergi berat, alergi terhadap dosis pertama vaksin COVID-19, dan hipersensitivitas terhadap komponen vaksin seperti PEG atau polisorbat 80. Pemberian vaksin mRNA COVID-19 memerlukan saran dari spesialis pada pasien dengan riwayat alergi terhadap polisorbat 80 karena kemungkinan reaktivitas silang dengan PEG. Alergi terhadap obat-obatan, makanan, allergen, inhalan, dan lateks bukan merupakan kontraindikasi vaksin COVID-19.[2]
Manajemen Vaksin COVID-19 Dosis Kedua dengan Reaksi Alergi Dosis Pertama
Seseorang yang mengalami anafilaksis terhadap vaksin COVID-19 tidak boleh menerima dosis kedua dari vaksin tersebut atau vaksin lain dengan eksipien serupa. Namun untuk pasien dengan reaksi alergi yang tidak memenuhi kriteria anafilaksis setelah dosis pertama, seperti urtikaria dan angioedema direkomendasikan untuk konsultasi ke dokter spesialis yang bersangkutan.[2]
Jika gejala pasien menunjukkan reaksi alergi yang dimediasi IgE namun tidak memenuhi kriteria anafilaksis maka uji tusuk kulit atau uji intradermal dengan reagen penyebab potensial dapat dipertimbangkan sebelum melakukan vaksinasi lanjut. Namun, tes kulit dapat dikaitkan dengan reaksi sistemik dan masih belum diketahui apakah alergi disebabkan oleh PEG dan polisorbat 80 adalah satu-satunya penyebab reaktivitas alergi terhadap vaksin COVID-19. Berdasarkan hasil tes kulit dan kondisi klinis kesehatan individu, pengambilan keputusan dapat dilakukan bersama dengan pasien.[2,8]
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) merekomendasikan bahwa pertukaran produk vaksin COVID-19 dalam situasi tertentu dapat dipertimbangkan pada kondisi tertentu dengan interval minimal 28 hari jika dosis pertama vaksin mRNA COVID-19. Pemberian vaksin adenovirus dapat diberikan sebagai dosis kedua jika tidak dapat menyelesaikan vaksin mRNA COVID-19 (strategi mix-and-match vaccine) karena kontraindikasi seperti alergi berat atau anafilaksis. CDC juga menyarankan bahwa pasien dengan kontraindikasi vaksin COVID-19 berbasis vektor adenovirus (seperti reaksi alergi polisorbat) dapat mempertimbangkan vaksin mRNA COVID-19 dengan hati-hati karena adanya kemungkinan reaksi silang antara PEG dan polisorbat.[9]
Premedikasi dengan antihistamin dan/atau kortikosteroid belum terbukti dapat mengurangi risiko reaksi alergi berikutnya. Sebaliknya, premedikasi dapat menutupi gejala kulit dan menyebabkan keterlambatan deteksi dan pengelolaan reaksi alergi yang parah. Namun, pengobatan awal dengan antihistamin generasi kedua sebelum dosis kedua vaksinasi COVID-19 dapat dipertimbangkan pada individu dengan gejala alergi ringan.[10]
Reaksi alergi termasuk anafilaksis dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, vaksinasi harus diberikan di bawah pengawasan medis yang ketat dan semua subjek harus diobservasi setidaknya selama 15 menit setelah vaksinasi. Sedangkan bagi pasien yang memiliki riwayat anafilaksis akibat alergi lainnya perlu diobservasi setidaknya 30 menit setelah vaksinasi. Beberapa obat dan kofaktor yang dapat memperburuk reaksi anafilaksis adalah beta-blocker seperti metoprolol. Tenaga medis perlu informasikan pasien tentang kofaktor anafilaksis pada hari injeksi dan menyarankan pasien untuk menghindarinya.[2]
Manajemen Anafilaksis Akut
Anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit dari kulit atau mukosa mulut ke keterlibatan multiorgan seperti dispnea, mengi, kram perut, muntah, dan kolaps sirkulasi. Oleh karena itu, pada tanda-tanda awal anafilaksis perlu segera diberikan suntikan epinefrin intramuskular serta menilai dan mempertahankan jalan nafas, pernafasan, sirkulasi dan status mental. Dosis epinefrin yang direkomendasikan adalah 0,01 mg/kg berat badan hingga dosis total maksimum 0,5 mg untuk orang dewasa dan 0,3 mg untuk anak-anak prapubertas. Epinefrin intramuskular dapat diulang setiap 5-15 menit jika gejala refrakter terhadap pengobatan.[2,7]
Setelah pemberian epinefrin pada kasus anafilaksis, pasien diposisikan terlentang dan diberikan suplementasi oksigen. Akses intravena dan penggantian volume dengan cairan isotonik dapat diberikan pada kasus dengan ketidakstabilan kardiovaskular. Pemberian glukagon parenteral dapat digunakan pada pasien dengan anafilaksis yang tidak memberikan respon optimal terhadap epinefrin, terutama pada pasien yang memakai beta-blocker.
Pengobatan seperti antihistamin (cetirizine) dan glukokortikoid (metilprednisolone) dapat diberikan untuk mengendalikan reaksi alergi lainnya pada kulit dan mukosa tetapi bukan sebagai terapi utama. Sebagian besar kasus anafilaksis memiliki onset gejala dalam waktu 30 menit setelah paparan. Semua pasien yang divaksinasi harus di edukasi tentang tanda-tanda anafilaksis dan jika mereka mempunyai gejala tersebut ini setelah meninggalkan pusat vaksin diharapkan untuk mencari bantuan medis segera.[2]
Pasien dengan gejala pernafasan harus dipantau secara ketat setidaknya selama 6-8 jam, dan mereka yang mengalami hipotensi memerlukan pemantauan ketat setidaknya 12-24 jam. Semua pasien dengan anafilaksis atau dugaan reaksi alergi harus dirujuk ke dokter spesialis alergi untuk penilaian yang lebih dalam. Pasien tidak boleh menerima dosis kedua vaksin kecuali dokter spesialis alergi memastikan bahwa vaksin bukan penyebab reaksi anafilaksis yang dialami pasien dan sebaiknya tetap dilakukan pada lokasi penyuntikkan vaksin dengan fasilitas medis yang memadai untuk menangani reaksi anafilaksis.[7]
Kesimpulan
Di tengah pandemi akibat virus corona, vaksinasi merupakan intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif. Seiring dengan meluasnya vaksinasi COVID-19, pemantauan ketat terhadap efek samping vaksin secara bersamaan dilakukan di seluruh dunia. Meskipun sebagian besar KIPI disebabkan oleh respons imun protektif yang dirangsang oleh vaksin, reaksi alergi parah yang jarang terjadi seperti anafilaksis juga dapat terjadi.
Walaupun insiden anafilaksis yang rendah, sangat dianjurkan untuk tetap melaporkan kasus anafilaksis terkait vaksinasi ke sistem pengawasan nasional agar dapat dianalisis lebih lanjut. Semua dokter yang terlibat dalam program vaksinasi COVID harus cepat mengenali dan mengobati anafilaksis, dengan persediaan epinefrin IM yang memadai.