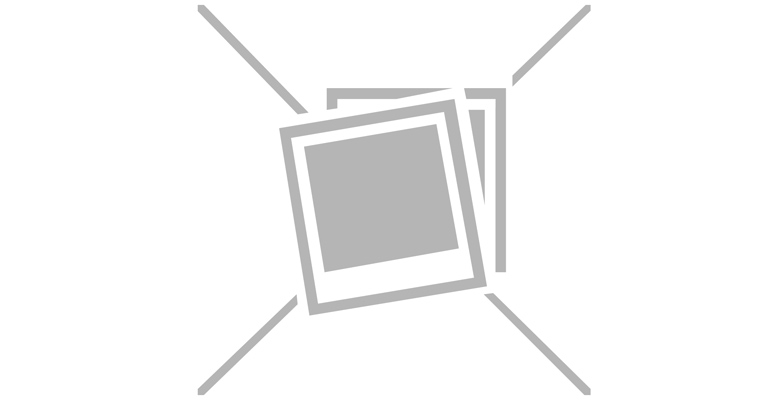Diagnosis Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)
Diagnosis acute respiratory distress syndrome (ARDS) pada umumnya dapat ditegakkan bila penyebab kardiogenik dan etiologi lain yang dapat menyebabkan hipoksemia akut telah disingkirkan, Diagnosis juga bisa dilakukan berdasarkan kriteria Berlin yang memandang onset, rasio PaO2/FIO2 pada penggunaan ventilator atau SpO2/FIO2 pada penggunaan high flow nasal cannula (HFNC), dan gambaran radiologi.[1-3]
Anamnesis
Anamnesis pada pasien ARDS umumnya dilakukan untuk mencari faktor penyebab. Keluhan utama pada pasien ARDS adalah dispnea dan hipoksemia akut. Onset umumnya dalam 12-48 jam atau beberapa hari setelah faktor penyebab terjadi. Beberapa faktor penyebab yang harus ditanyakan adalah trauma, sepsis, overdosis obat, transfusi, dan tersedak.
Dispnea umumnya ditemukan pada saat ekspirasi pada fase awal dan dapat mengalami perburukan menjadi dispnea saat istirahat hingga gasping. Kegagalan multiorgan juga dapat terjadi pada fase awal. Pasien yang dapat melewati fase awal dengan baik pada umumnya akan mengalami perbaikan oksigenasi dan ventilasi.
Pada fase lanjut, pasien yang masih mengalami hipoksemia persisten dan bergantung dengan ventilator pada umumnya akan mengalami gagal napas. Hal ini umumnya terjadi setelah 10 hari. Fungsi paru juga semakin memburuk, ditandai dengan penurunan komplians paru, peningkatan dead space, dan hipertensi pulmonal.[1-3]
Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan fisik pada pasien ARDS dapat menunjukkan kelainan terkait respirasi, seperti takipnea dan peningkatan usaha napas dengan penggunaan otot bantu napas. Tanda klinis umum pasien dapat berbeda sesuai derajat keparahan ARDS, seperti sianosis, takikardia, dan penurunan status mental. Ronkhi dapat ditemukan pada auskultasi dada.
Suhu pasien dapat terukur hipertermik maupun hipotermik. ARDS juga dapat disertai dengan syok yang menyebabkan hipotensi dan akral dingin akibat vasokonstriksi perifer. Pada pasien dengan sepsis, pemeriksaan fisik perlu mencari sumber infeksi, seperti pada luka operasi, pemasangan drain, ulkus dekubitus, infus intravena, maupun sumber infeksi lainnya.[1-3]
Diagnosis Banding
Dua diagnosis banding utama dari ARDS adalah edema paru kardiogenik dan non-kardiogenik.[1-3]
Edema Paru Kardiogenik
Edema paru kardiogenik adalah kondisi yang disebabkan oleh gagal jantung. Cara membedakannya dengan ARDS adalah dengan melihat riwayat medis pasien.
Pasien dengan edema paru kardiogenik biasanya memiliki riwayat penyakit jantung atau hipertensi. Pemeriksaan fisik dapat mengungkapkan tanda-tanda seperti edema tungkai, terbatasnya mobilitas dinding dada, dan suara napas yang abnormal. Pemeriksaan elektrokardiogram (EKG) juga dapat membantu dalam diagnosis.[1-3]
Edema Paru Non-Kardiogenik
Edema paru non-kardiogenik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pneumonia, aspirasi, atau keracunan. Pembeda utamanya adalah dengan mengevaluasi riwayat medis dan gejala pasien. Radiografi toraks dan analisis gas darah akan membantu dalam membedakan antara ARDS dan edema paru non-kardiogenik.[1-3]
Emboli Paru
Emboli paru terjadi ketika trombus, yang biasanya terbentuk di kaki, terlepas dan masuk ke pembuluh darah paru dan menyumbat aliran darah. Kondisi ini dapat menghasilkan gejala mirip ARDS, seperti sesak napas, nyeri dada, dan takikardia. Diagnosis emboli paru dapat dilakukan dengan CT pulmonary angiography (CTPA) atau VQ scan, yang akan menunjukkan adanya trombus di pembuluh darah paru.[1-3]
Pemeriksaan Penunjang
Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien ARDS adalah pemeriksaan laboratorium, terutama analisis gas darah, dan pencitraan radiologi, terutama rontgen toraks.
Pemeriksaan Laboratorium
Pemeriksaan laboratorium utama dalam penegakan diagnosis ARDS adalah pemeriksaan analisis gas darah (AGD). Pemeriksaan AGD dilakukan untuk memenuhi salah satu Kriteria Berlin dalam penegakan diagnosis ARDS, yaitu rasio PaO2/FIO2. Rasio PaO2/FIO2 juga digunakan untuk mengetahui derajat keparahan penyakit. Selain itu, pada analisis gas darah, dapat ditemukan kondisi hipoksemia dan alkalosis respiratorik.
Untuk menyingkirkan diagnosis banding edema paru, pemeriksaan brain natriuretic peptide (BNP) atau NT-proBNP dapat dilakukan. Pemeriksaan hematologi juga dapat menunjukkan kelainan lainnya, seperti leukopenia, leukositosis, maupun trombositopenia pada pasien sepsis, serta peningkatan kadar berbagai sitokin.[1-3,9-12]
Pencitraan
Pada rontgen toraks akan ditemukan opasitas bilateral yang tidak dapat didefinisikan sebagai efusi, kolaps, atau nodul pada pencitraan radiologi. Temuan ini juga dapat terlihat pada pencitraan dengan computed tomography (CT).
Infiltrat bilateral dapat simetris maupun tidak simetris dan dapat dipengaruhi oleh penyakit yang mendasari terjadinya ARDS. Infiltrat ini dapat ditemukan bertambah buruk dalam waktu yang singkat, biasanya mencapai kondisi parah dalam tiga hari. Infiltrat dapat berbentuk difus dengan tampilan ground glass.
Selain pencitraan dada dengan rontgen atau CT, pemeriksaan lain, seperti echocardiography dapat diperlukan. Pemeriksaan echocardiography dilakukan untuk menilai dan menyingkirkan kemungkinan edema paru yang disebabkan oleh kelainan jantung. Selain itu, echocardiography juga dapat memberikan informasi mengenai adanya disfungsi ventrikel kanan yang dapat menjadi pertimbangan penentuan kuantitas penggunaan cairan dalam penatalaksanaan ARDS.[1-3,9-12]
Kriteria Penegakan Diagnosis
Kriteria yang digunakan dalam penegakan diagnosis ARDS adalah Kriteria Berlin yang telah dipakai sejak 2012. Namun, modifikasi Kigali juga digunakan untuk melengkapi Kriteria Berlin, terutama sejak mulainya Pandemi COVID-19. Penggunaan rasio SpO2/FIO2 mulai banyak digunakan sebagai penilaian kriteria oksigenasi karena tidak invasif dan tersedia luas bila dibandingkan dengan rasio PaO2/FIO2. [1,10-13]
Tabel 1. Kriteria Berlin
| Onset | Onset akut dalam 1 minggu |
| Etiologi | Gagal napas yang tidak dapat dijelaskan oleh kelainan fungsi jantung atau overload cairan |
| Pencitraan | Opasitas bilateral pada rontgen atau CT thorax yang tidak dapat dijelaskan oleh efusi, kolaps, atau nodul |
| Oksigenasi | Hipoksemia akut dengan PaO2/FIO2 <300 mmHg pada penggunaan ventilator dengan PEEP setidaknya 5 cmH2O |
Sumber: dr. Michael Sintong Halomoan, Alomedika, 2023.[10]
Tabel 2. Modifikasi Kigali
| Onset | Sama dengan Kriteria Berlin |
| Etiologi | Sama dengan Kriteria Berlin |
| Pencitraan | Opasitas bilateral pada rontgen, CT, atau USG thorax yang tidak dapat dijelaskan oleh efusi, kolaps, atau nodul |
| Oksigenasi | Hipoksemia akut dengan SpO2/FIO2 <315 mmHg tanpa aturan PEEP tertentu |
Sumber: dr. Michael Sintong Halomoan, Alomedika, 2023.[1]
Derajat ARDS dapat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu:
- ARDS ringan dengan rasio PaO2/FIO2 201 - 300 mmHg
- ARDS sedang dengan rasio PaO2/FIO2 101 - 200 mmHg
- ARDS berat dengan rasio PaO2/FIO2 ≤100 mmHg[1,10-13]
Penulisan pertama oleh: dr. Josephine Darmawan